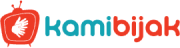Kampong Lorong Buangkok, Desa Terakhir yang Bertahan di Singapura
Kamis, 03 Juni 2021 -
JIKA kamu meninggalkan Jalan Yio Chu Kang yang sibuk di timur laut Singapura, lalu mengikuti jalan tanah yang panjang yang berkelok-kelok sejauh sekitar 300m, bersiaplah masuk ke dalam kapsul waktu. Di atas lahan hijau seluas tiga hektare berdirilah Kampong Lorong Buangkok, desa terakhir yang masih bertahan di Singapura.
Di tempat ini, sisa-sisa tahun 1960-an masih hidup dan terpampang nyata. Di sekelilingnya, Singapura modern dengan gedung-gedung pencakar langit tampak menjulang sebagai latar belakang. Secara kontras, di hadapanmu akan berdiri rumah-rumah bungalow kecil yang bagaikan keluar dari kartu pos antik zaman dulu.
Kampong Lorong Buangkok merupakan oasis pedesaan dengan sekitar 25 rumah kayu satu lantai dengan pola dasar atap seng tersebar di sekitar surau. Tumbuhan lokal – seperti ketapang, pohon asli pesisir – bermunculan dari tanah yang terlupakan. Tanah yang dulu pernah menutupi Singapura sebelum "ditumbuhi" beton. Di sana juga masih terlihat kabel listrik menggantung di atas kepala. Itu menjadi pemandangan yang langka karena sebagian besar kabel telah berada di bawah tanah di seluruh kota.
>Baca juga: >Bangsal Witana, Cikal Bakal Keraton Cirebon
Penduduk lansia duduk di beranda mereka; ayam di kandang mereka berkokok tanpa henti; dan paduan suara jangkrik berkicau dan ayam jantan berkokok. Suara zaman dulu itu meredam polusi suara kota dan memberikan musik latar pedesaan yang menenangkan.
Tidak ada yang pernah mengindentifikasi Singapura dari pemandangan Kampong Lorong Buangkok. Negara kota ini identik dengan menara Marina Bay Sands yang berbentuk perahu, atau Gardens by the Bay yang penuh warna dan futuristik. Namun, hingga awal 1970-an, kampung seperti Lorong Buangkok ada di mana-mana di seluruh Singapura. Peneliti dari National University of Singapore memperkirakan, dulu ada sebanyak 220 kampung yang tersebar di pulau yang sama. Saat ini, sementara beberapa masih ada di pulau-pulau sekitar, Lorong Buangkok adalah desa terakhir di pulau utama.
Kampung yang (Tidak) Mengalah

Sebuah negara muda dengan aspirasi internasional, Singapura dengan cepat mengalami urbanisasi pada 1980-an dan dengan cepat beralih dari ekonomi pertanian ke industri. Ruko-ruko yang penuh sesak digantikan dengan flat bertingkat tinggi dan gedung pencakar langit yang luas, mengantarkan apa yang disebut "era jalan tol" yang melihat jalan-jalan kecil diganti dengan jalan raya multi-jalur melintasi si negara-kota. Dengan tanah yang mahal di pulau itu, kampung-kampung pedesaan harus mengalah.
Maka ratusan desa tradisional dibuldoser, flora asli dilucuti, jalan tanah diratakan dan mata pencaharian diratakan dengan tanah sebagai bagian dari program pemukiman pemerintah. Penduduk desa, beberapa enggan, menyerahkan tanah-tanah mereka yang berharga; yang lain ingin menukar kehidupan pedesaan dengan kehidupam modern di flat bersubsidi yang dibangun pemerintah yang didirikan di atas rumah lama mereka. Saat ini, lebih dari 80 persen orang Singapura tinggal di flat-flat tersebut.
Baca juga:
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia Dipamerkan di Dubai
Salah satu alasan Lorong Buangkok berhasil lolos dari nasib yang menimpa kampung-kampung lain adalah karena daerah sekitarnya tidak begitu diinginkan untuk pengembangan komersial, industri dan perumahan seperti di tempat lain di Singapura. Meskipun, akhirnya kondisi itu perlahan berubah. Dulu kampung itu dikelilingi oleh pembukaan hutan dan pertanian, sekarang diapit oleh perumahan berpagar pribadi dan sekelompok flat yang menghadap ke pemukiman bertingkat rendah.
Namun, ada alasan lain, yaitu tanah desa ini dimiliki oleh seorang perempuan keras kepala dengan komitmen teguh untuk melestarikan satu-satunya kampung yang masih hidup di Singapura.
Mendekati 70 tahun, Sng Mui Hong, telah menjalani hampir seluruh hidupnya di desa. Ia adalah anak bungsu dari empat bersaudara, dan satu-satunya yang pernah tinggal di sini. Almarhum ayahnya, seorang penjual obat tradisional Tiongkok, membeli tanah itu pada tahun 1956, tahun yang sama ketika desa itu dibuat dan sembilan tahun sebelum Singapura merdeka.

Menurut pemandu lokal Kyanta Yap, yang memimpin tur keliling kampung, sebagian besar petak disewakan kepada pekerja dari rumah sakit terdekat dan perkebunan karet – banyak dari keturunannya masih tinggal di sini. Saat itu, sewa bulanan untuk setiap rumah berkisar antara S$4,50 dan S$30 atau sekitar Rp50.000 - Rp300.000.
Hari ini, Sng masih membebankan tarif yang kurang lebih sama kepada 25 keluarga Lorong Buangkok. Sebaliknya, menyewa kamar yang kira-kira sepersepuluh ukuran rumah kampung di blok bangunan pemerintah yang berdekatan mungkin menelan biaya sekitar 20 kali lipat dari jumlah itu. Dan rumah-rumah di seberang kanal pemisah dapat dijual dengan harga beberapa juta dolar Singapura.
Meskipun desa ini memiliki harga sewa paling terjangkau di Singapura, tidak ada penghuni baru yang pindah sejak tahun 1990-an, dan kecil kemungkinannya akan ada dalam waktu dekat. Karena menurut Yap, seseorang harus pindah atau meninggal dunia agar rumah itu kosong. Namun setelah itu mereka yang memiliki hubungan dengan penyewa dulu akan diprioritaskan untuk menyewa. (Aru)
Baca juga:
Perbukitan dan Pegunungan di Sleman jadi Destinasi Wisata Favorit