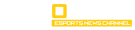Kekejaman Tanam Paksa di Lebak Banten dalam Karya Sastra 'Max Havelaar'
Sabtu, 07 Mei 2016 -
Merahputih Budaya - 'Max Havelaar' sebuah karya sastra berbentuk novel yang ditulis Multatuli di musim dingin, di sebuah losmen di Belgia tahun 1859. Naskah diselesaikan Multatuli dalam satu bulan.
Kemudian Max Havelaar untuk pertama kalinya terbit tahun 1860. Kemunculannya mengundang banyak perhatian dan banyak diperbincangkan oleh para kritisi sastra dunia. Secara tidak langsung pula, nama Lebak (sebagai bagian dari Indonesia) menjadi buah bibir orang-orang diberbagai dunia.
Novel ini terbit dalam bahasa Belanda dengan judul asli "Max Havelaar, of de koffij-veilingen der Nederlandsche Handel-Maatschappij" (bahasa Indonesia: "Max Havelaar, atau Lelang Kopi Perusahaan Dagang Belanda")
Roman ini hanya ditulis oleh Multatuli dalam tempo sebulan pada tahun 1859 di sebuah losmen di Belgia. Setahun kemudian, tepatnya pada tahun 1860 roman itu terbit untuk pertama kalinya.
Karena Max Havelaar dunia membaca Indonesia (kala itu masih nusantara dalam penyebutan daerah terbagi banyak pulau) dari segala sudut pandang seperti Politik, ekonomi, budaya, dan sikologis masyarakat Indonesia.
Untuk kemudian setelah kemunculannya yang menggemparkan sekian lama, barulah Indonesia menerima subsidi dari pemerintah Belanda tahun 1972 bertepatan dengan tahun buku internasional.
Di Indonesia, karya ini sangat dihargai karena untuk pertama kalinya inilah karya yang dengan jelas dan lantang membeberkan nasib buruk rakyat yang dijajah. Max Havelaar bercerita tentang sistem tanam paksa yang menindas kaum bumiputera di daerah Lebak, Banten. Max Havelaar adalah karya besar yang diakui sebagai bagian dari karya sastra dunia. Di salah satu bagiannya memuat drama tentang Saijah dan Adinda yang sangat menyentuh hati pembaca, sehingga sering kali dikutip dan menjadi topik untuk dipentaskan di panggung.
Mendapat kesan pada cetakan pertama yang baik, meski dengan segala kekurangannya. Selang satu tahun cetakan kedua menyusul tahun 1973, dengan ejaan yang telah disempurnakan. Dan pada cetakan selanjutnya pula, Dr Gerard Termorshuizen membut kata pendahuluan yang baru dengan anotasi yang ditambah dengan begitu teliti. Sebagai pembuktian bahwa karya sastra yang berkualitas tidak termakan zaman. (Dul)
BACA JUGA: