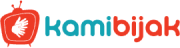Bedah Ancaman Koalisi Gemuk Jokowi Jilid 2, Kolesterol sampai Komplikasi
Senin, 08 Juli 2019 -
MerahPutih.com - Koalisi Indonesia Adil Makmur pendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno pada Pilpres 2019 telah membubarkan diri setelah Komisi Pemilihan Umum (KPU) resmi menetapkan rivalnya Joko Widodo (Jokowi) dan Ma'ruf Amin sebagai presiden dan wakil presiden terpilih.
Koalisi ini sebelumnya didukung oleh Partai Gerindra, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Demokrat. Belakangan santer terdengar bahwa keempat partai tersebut bakal merapat ke kubu pendukung pemerintah.
BACA JUGA: Tawaran Koalisi Kubu Jokowi Strategi Kubur Masa Depan Gerindra di 2024
Koalisi pasca Pilpres memang memiliki tingkat kerumitan tersendiri. Meski seorang capres bisa mendapat suara signifikan dalam pilpres, dukungan politik di parlemen nanti tak bisa diabaikan agar pemerintahan berjalan efektif. Logika matematika politik tak bisa dipungkiri memengaruhi pola koalisi pascapilpres.
Kabar Buruk Bagi Demokrasi

Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi menilai isu rekonsiliasi memaksa Jokowi untuk melakukan pendekatan kepada partai di luar koalisi pendukungnya. Menurut dia, bergabungnya partai-partai oposisi ke kubu pemerintah akan menimbulkan komplikasi demokratik.
"Kalau semua partai di luar (pemerintah) setelah pemilu kemudian masuk dalam gelanggang kekuasaan buat apa ada Pemilu? Pemilu itu kan gunanya untuk menguji narasi program yang ditawarkan masing-masing kubu," kata Burhan saat ditemui MerahPutih.com, di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Minggu (7/7).
Partai-partai pemenang pilpres, kata Burhan, idealnya berada "di dalam" untuk mengelola pemerintahan, sementara "yang di luar" merepresentasikan pihak yang kalah sehingga harus menjadi blok oposisi di parlemen.
"Menjadi oposisi dalam konstruksi demokratis itu sama bijaknya secara demokratik," imbuh pria kelahiran Rembang ini.

Namun, kata Burhan, perilaku partai politik di Indonesia tidaklah selinier yang dibayangkan. Nafsu politisi untuk selalu berada di dalam gerbong kekuasaan akan membuat peta koalisi rentan berubah. Ia lantas mencontohkan Golkar, sejak Pilpres 2004 hingga 2014 capres yang diusung partai beringin selalu kalah, namun Golkar tetap masuk dalam koalisi pendukung pemerintah.
"Kalau kemudian Gerindra, Demokrat dan PAN masuk dalam gelanggang kekuasaan, oposisi jadi sepi peminat, itu jadi kabar buruk buat demokrasi. Karena fungsi oposisi sebagai penyampai alternatif yang kredibel itu tidak terjadi. Dan Akhirnya kekuasaan menjadi sangat hegemonik," jelas Burhan.
Tiga Paket Pilihan Koalisi Jokowi

Peraih gelar doktor dari Departement of Political and Social Change, Australian National University (ANU) ini menjelaskan, secara teoritis, Jokowi sebagai pemenang pilpres bisa memilih tiga paket besaran koalisi: koalisi mini (minority coalition), koalisi ramping (minimal winning coalition), dan koalisi maksi (oversized coalition).
Koalisi mini terlalu berisiko karena posturnya terlalu kecil untuk mendukung pemerintahan di parlemen. Hal itu tampak pada periode awal pemerintahan Jokowi jilid satu. Ketika dilantik pada Oktober 2014, Jokowi memiliki kepercayaan diri yang tinggi untuk membentuk formasi kabinet berdasarkan kabinet minimalis. Secara politik, Jokowi hanya bertumpu pada empat partai PDI-P, NasDem, PKB dan Hanura dengan jumpah total kursi 37 persen di DPR.
BACA JUGA: Koalisi Jokowi-Ma'ruf Tidak Perlu Ada Penambahan Partai
Jokowi, kata Burhan, saat itu menjadi "presiden minoritas" dalam tiga lapis sekaligus: figur baru yang langsung melejit ke pentas nasional, tidak memiliki kendali atas partainya sendiri dan hanya mengandalkan koalisi ramping di parlemen. Alhasil, pemerintahan menjadi tidak efektif karna partai koalisi di parlemen tak mampu mengamankan program-program pemerintah.
Sebaliknya, koalisi obesitas juga terbukti tidak efektif seperti pengalaman pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) jilid kedua yang diusung 75 persen kekuatan politik di parlemen, tetapi ibarat seseorang yang "kegemukan" gerak komunikasi Setgab kala itu terlalu lamban dan sakit-sakitan.
"Kalau misalnya Demokrat masuk, PAN masuk, Gerindra masuk, disisakan PKS justru yang terjadi koalisi itu obesitas. Ibarat orang yang terlalu gemuk, tak lincah dalam bergerak dan akibatnya banyak lemak jahat yang membuat disipilin koalisi lemah. Dan ketika disipilin koalisi melemah yg terjadi adalah presiden gagal memanage koalisinya," papar Burhan.

"Terlalu banyak kolestrol politik yang mengakibatkan Pak SBY saat itu gagal melakukan proses disiplin koalisi yang solid. Dan akibatnya Golkar dan PKS dengan manuver isu centurynya turut menggrogoti legitimasi dan aproval rating Pak SBY. Bukan tidak mungkin Gerindra ditarik, Demokrat ditarik, PAN ditarik, fisiknya ada di koalisi tapi hatinya ada di oposisi," imbuh dia.
Burhan menyebut salah satu alasan partai-partai oposisi tergiur masuk ke koalisi pemerintah karena dengan skema Undang-undang 2/2018 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3), Jokowi bukan hanya menang Pilpres tapi juga menang di Pileg, dengan kompososi partai koalisinya mencapai dari 60%. Dengan demikian, pimpinan komisi di parlemen akan disapu bersih oleh partai pendukung Jokowi.
Ketentuan komposisi pimpinan DPR yang diatur UU MD3 menguatkan posisi kubu Jokowi. Pasal 427 UU tersebut menyatakan Ketua DPR periode depan akan dijabat anggota DPR yang berasal dari partai pemilik kursi terbanyak pertama di DPR. Sedangkan empat wakil ketua DPR dijabat empat anggota DPR yang berasal dari partai yang memperoleh kursi terbanyak kedua, ketiga, keempat, dan kelima.
BACA JUGA: Ingatkan Jokowi-Prabowo, Presiden PKS: Bagi-Bagi Kursi Menyakiti Rakyat
Partai pemilik kursi terbanyak pertama di DPR ialah PDIP (125 kursi). Sementara partai yang memperoleh kursi terbanyak kedua, ketiga, keempat, dan kelima, secara berurutan yakni, Golkar, Gerindra, Nasdem, dan PKB. Tak hanya kalah dalam perolehan kursi di DPR, dari empat partai pengusung Prabowo-Sandia, hanya Gerindra saja yang kemungkinan besar mendapat posisi pimpinan DPR.
"Supaya partai oposisi komit berada di luar pemerintahan dan tidak tergoda masuk ke pemerintahan berikan mereka insentif, apa insentifnya? pimpinan komisi di parlemen jangan di sapu bersih sama kekuatan Pak Jokowi," tutur Burhan.
Menurut Burhan, yang ideal untuk dipertimbangkan Jokowi adalah koalisi ramping tapi sehat. Postur koalisi tidak terlalu besar tapi secara matematis mampu mengunci single majority di parlemen. Jika disiplin koalisi bisa dijalankan, minimal winning coalition bisa menyokong pemerintahan secara efektif.
Ramping tapi Lincah

Kabinet ahli lebih leluasa terbentuk dan portfolio kementerian tak perlu ditransaksikan secara berlebihan kepada menteri menteri dari partai yang tidak punya kompetensi. Pertarungan gagasan lebih dimungkinan terjadi di parlemen karena proposal ide dan kebijakan akan saling dipertukarkan.
"Pendukung Pak Jokowi saat ini telah memperoleh kurang lebih 60% kursi di DPR artinya sudah mayoritas, berbeda dengan 2014, Pak Jokowi didukung hanya dengan kekuatan 37% kekuatan di parlemen artinya minority coalition. Kalau ingin solid itu jangan terlalu ramping juga, tapi jangan terlalu gigantic, misalnya dengan mengandalkan yang sekarang saja ada itu sudah cukup the winning coalition sekitar 60%," ujar Burhan.
BACA JUGA: Gerindra Bocorkan Waktu Pertemuan Prabowo dan Jokowi
Burhan mengingatkan, koalisi pemerintah yang terdiri dari 5 partai dan mencapai 60 % di parlemen potensial menjadi kekuatan hegemonik yang bisa melumpuhkan sikap kritis DPR terhadap pemerintah. Untuk itu, ia menyarankan Jokowi tak perlu tergoda lagi menambah armada baru koalisi.
"Koalisi yang terlalu besar malah membuat langkah Jokowi kurang lincah karena harus menegosiasikam setiap kebijakan yang mau diambil kepada aktor yang makin banyak. Jokowi cukup melakukan disipilin koalisi yang kuat agar koalisi pemerintah yang mendukungnya efektif dalam menjalankan agenda pemerintahan," paparnya.
Namun, kata Dosen Ilmu Politik, FISIP UIN Syarif Hidayatullah ini, jika koalisi maksi menjadi pilihan, harga sosial politiknya terlalu mahal. Pemerintah, lanjut Burhan, akan tersandera secara politis dan tercipta "kecemburuan" kepada aktor dan partai yang tak berkeringat dalam pilpres, tapi ikut menghisap "madu" pemerintahan.
"Saya nggak yakin partai koalisi Pak Jokowi rela memberikan jatah pemberian kepada partai oposisi yang masuk ke koalisi pendukung pemerintah," tutup Burhan. (Pon)
BACA JUGA: Kronologi Maju Mundur Rekonsiliasi Prabowo-Jokowi