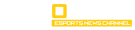Indonesia Darurat Hoaks
Rabu, 03 Oktober 2018 -
INDONESIA darurat hoaks. Setidaknya isu tersebut terjadi akhir-akhir ini. Beberapa tahun yang lalu, tak banyak orang yang menggunakan istilah hoaks. Namun kini, hoaks menjadi ancaman nyata bagi perkembangan informasi, demokrasi, atau kebebasan beropini. Hoaks merupakan kata serapan dari bahasa Inggris yaki hoax. dalam Kamus Oxford hoax didefinisikan sebagai malicious deception atau kebohongan yang dibuat dengan tujuan jahat.
Hoaks atau berita palsu telah beredar sejak tahun 1439 kala Johannes Gutenberg menciptakan mesin cetak. Namun, perkembangan teknologi informasi membuat persebaran berita hoaks lebih masif dan menyeluruh.
Kamus Oxford telah mengumumkan bahwa kata hoaks menjadi Word of the Year 2016. Sejumlah informasi hoax yang beredar di masyarakat seolah menjadi bom waktu yang bisa menyerang kapan saja. Kesimpangsiuran suatu informasi dapat menyebabkan keresahan hingga provokasi di kalangan warganet. Tak jarang berita hoax juga membuat orang saling lempar argumen hingga berakhir bentrok.

Orang-orang yang rentan terpapar berita hoaks yakni orang-orang yang tidak suka membaca dan jarang mengonsumsi berita. Ketika mereka mengetahui berita hoaks, dengan mudahnya mereka meyakini bahwa berita tersebut nyata. Mereka langsung mempercayai konten berita hoaks tersebut tanpa mengklarifikasi terlebih dahulu karena enggan. Diskusi tentang berita palsu telah memunculkan fokus baru pada literasi media secara lebih luas.
Berpikir kritis merupakan kunci dalam literasi media dan informasi sehingga kita bisa mendapatkan informasi yang faktual dan teruji kebenarannya. International Federation of Library Association and Institutions (IFLA) pun turut ambil bagian untuk mengendalikan persebaran berita hoaks yang semakin meluas. Sebagai pustakawan, IFLA menghimbau masyarakat untuk memiliki keterampilan untuk menavigasi informasi yang beredar sebelum mempercayainya.
Ada tujuh langkah yang bisa dilakukan untuk mendeteksi berita palsu:
1. Mengetahui Sumber

Hal yang pertama yang bisa dilakukan adalah megetahui sumber berita yang beredar. Kita bisa mencaritahu profil sumber berita. Dengan begitu kita bisa mengetahui akurasi dari berita yang beredar.
2. Cari Tahu Sumber Pendukung

Dalam suatu artikel, penulis biasanya memperkuat data yang ada dengan memasukkan sejumlah sumber pendukung. Cari tahu pula profil tentang sumber pendukung tersebut dengan browsing terlebih dahulu di internet. Dengan demikian, kita bisa mengetahui seberapa akurat berita yang ditampilkan.
3. Baca Keseluruhan Berita

Terkadang, penulis sengaja membuat judul berita yang bombastis supaya warganet tergoda untuk membaca tulisannya. Namun terkadang judul yang dibuat tidak sesuai dengan konteks tulisan. Pastikan berita yang kita baca tidak clickbait. Clickbait adalah ketidaksinambungan antara judul dengan artikel secara keseluruhan.
4. Cek Penulis

Periksa siapa yang membuat tulisan tersebut. Apakah mereka kredibel atau tidak. Orang-orang yang menulis secara anonim biasanya dipertanyakan kebenaran isi beritanya,
5. Cek Waktu

Tak semua berita hoaks itu palsu. Ada pula beberapa berita benar namun disebarkan di waktu yang tidak tepat. Tujuannya untuk menciptakan gelombang di masyarakat dan menimbulkan provokasi. Cek tanggal penulisan dan tanggal peristiwa berlangsung. Cari tahu sumber lain yang membahas masalah serupa apakah waktu penulisan tepat atau tidak. Jika berita tersebut terjadi beberapa tahun lalu dipastikan berita tersebut masuk kategori hoaks.
6. Pastikan Berita Bukan Lelucon

Berita hoaks terkadang dibuat oleh orang yang iseng. Mereka tidak memperkirakan dampak yang akan terjadi di masyarakat karena tujuannya hanya keisengan belaka. Untuk itu pastikan bahwa berita bukan hanya tipuan dan lelucon.
7. Tanyakan Ahlinya

Tanyakan pada ahlinya misalnya akademisi, praktisi di bidang tertentu yang sesuai dengan konten berita, pustakawan atau jurnalis. Mereka biasanya lebih paham dengan isu yang beredar di masyarakat dan mengetahui kebenarannya. (avia)