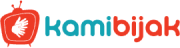Kurukshetra dan Kampung Begal
Sabtu, 18 Maret 2017 -
>Apa yang diungkapkan oleh warga kampung yang sudah setengah ludes itu, tetap saja akan menjadi cerita, dan hanya akan mewariskan peristiwa-peristiwa yang sama di kemudian hari. Buktinya, ketika hukum sudah tidak mampu merambah, mereka menganggap pengadilan masa dinilai mujarab untuk mencegah.
>Entah benar entah salah, tetapi, buat mereka, yang pasti hanya butuh hidup aman, tanpa seorang pun mengusik serta mengganggu. Bagaimana ceritanya? Lihat saja; tombak, parang, golok, badik, linggis, arit, bensin, korek api, dan segala rupa peralatan yang bisa dijadikan alat untuk membunuh, dibawa, dan seolah bisa membuat hidup mereka menjadi tenteram. >Konflik pun tidak bisa dihindari. Suasana kampung di pinggir perkebunan kelapa sawit itu menjadi seperti Padang Kurukshetra—tempat berlangsungnya perang Bharatayudha. Orang-orang yang menurut mereka ini adalah sebagai biang keladi—penyebab setiap kali sapi, kambing, atau motor itu raib entah ke mana—yang menjadi pemicunya. >Namun meskipun ia dituding sebagai pemicu, mereka bukanlah patung yang hanya diam jika dijewer, dicubit, ditonjok, ditendang, atau diludahi sekalipun. Ketika satu di antara mereka disakiti, semua ikut merasakan. Dari situlah, mereka melawan, bahkan akan menghimpun masa yang lebih besar lagi. Terlebih, mereka menilai tanah itu adalah milik moyangnya, yang telah turun-temurun beranak-pinak dan mewariskan generasi ke generasi. >“Ini adalah tanah moyang Kami! Kenapa Kami diusik? Kenapa Kami dituduh maling? Hutang nyawa dibayar nyawa!” Teriak mereka sepanjang jalan, sambil menghunus badik, golok, parang, dan tombak. >Mereka merasa dirinya adalah benar. Begitu pun sebaliknya, orang-orang yang kehilangan sapi, kambing, atau motor yang raib entah ke mana itu, juga mengaku apa yang mereka lakukan bukanlah sebuah kesalahan. >“Warga Kami sudah terlalu lama bersabar! Selama ini, sapi, kambing, atau motor Kami raib, mereka lah yang menggasak. Mereka itu para bencoleng, maling, begal! Mereka juga tinggal dalam satu kampung, yang isinya orang-orang yang sama. Kami jarang mendengar mereka ini ditangkap polisi, atau dipenjara. Kalau pun ada yang tertangkap, begitu gampang mereka melenggang keluar sebelum masa tahanannya habis di dalam penjara. Itu yang menjadikan warga Kami geram, dan mengambil langkah hukum dengan cara-cara Kami. Maksudnya, agar mereka tidak lagi mengusik Kami!” Ungkap salah seorang warga kampung setengah teriak. > >Bibir kampung itu pun, sudah dikepung polisi. Kawat berduri dililit menghadang beberapa akses jalan, agar kelompok orang-orang dari kampung yang disangkakan maling sapi, kambing, atau motor itu menyerang tidak bisa menerobos masuk ke dalam kampung. >Sementara, di dalam kampung sendiri sudah seperti kampung mati. Senyap, mencekam. Tak satu pun ada orang beraktivitas, seperti sebelum seorang yang dituduh maling itu tewas dengan luka memar, bacok, dan tubuh hangus terbakar. Kecuali, laki-laki dewasa yang berseliweran, siaga dengan tombak, parang, golok, badik, linggis, dan arit—siap menyambut serangan orang-orang yang selama ini dianggapnya sebagai hama perusak kampung. >Manula, anak kecil, dan para wanita sudah diungsikan di kampung-kampung sebelah—kampung yang tidak dihuni oleh orang-orang yang disangkakan sebagai maling dan begal. Sebagian diboyong ke masjid besar, dan pesantren. Maksudnya, agar mereka tetap aman, dan—jika tiba-tiba kampung itu diserang—tidak mungkin akan merambah ke dalam masjid atau pesantren, karena itu adalah rumah Tuhan. >Entah kenapa, semua menjadi semakin ruwet. Tiba-tiba ribuan orang dari kampung yang disangkakan sebagai kampung para bencoleng ini bisa merangsek ke dalam kampung. Mereka membabi buta. Barang-barang yang berada di dalam rumah yang kosong ditinggal mengungsi raib dijarah. Televisi, magic jar, baju, sarung, dan semua barang yang bisa ditenteng, digasak, sebelum rumah-rumah itu dirusak, dan dibakar. Sisa makanan yang tak sempat dibawa mengungsi, dilahap habis, rakus masuk ke dalam perut mereka. >“Aparat seperti macan ompong! Diam, tidak berkutik! Buktinya, pagar betis mereka diterobos! Kampung Kami dibiarkan ludes, dibakar oleh orang-orang dari kampung para bencoleng!” Keluh salah seorang warga kampung geram dengan bibir setengah bergetar. >“Benar! Kami juga tidak habis pikir, kenapa bisa seperti itu. Padahal, aparat-aparat itu membawa bedil,” sahut warga lainnya, dengan raut muka redup, dan putus asa. >Namun, apa yang diungkapkan oleh warga kampung yang sudah setengah ludes itu, tetap saja akan menjadi cerita, dan hanya akan mewariskan peristiwa-peristiwa yang sama di kemudian hari. Buktinya, ketika hukum sudah tidak mampu merambah, mereka menganggap pengadilan masa dinilai mujarab untuk mencegah. Entah benar entah salah, tetapi, buat mereka, yang pasti hanya butuh hidup aman, tanpa seorang pun mengusik serta mengganggu. > >Tak lain dan tak bukan, tewasnya salah seorang warga kampung yang disangkakan sebagai kampung para bencoleng di sudut kampung inilah yang menjadi puncak malapetaka, serta pecahnya perang dua kubu tersebut. Orang itu, tewas diamuk masa, serta dibakar, dan disaksikan oleh kepala kampung tersebut, lantaran dituduh mencuri sapi. >Kampung itu benar-benar sudah setengah rata dengan tanah. Kebulan asap dari puing-puing sisa reruntuhan, membekas, dan membuat kampung itu menjadi nampak semakin angker. Lebih dari separuh penghuni kampung pun, sudah tunggang-langgang sebelum kampung itu berubah seperti kampung sisa perang. >Wajah-wajah yang sebelumnya garang; menghunus badik, golok, arit, tombak, linggis, serta segala rupa peralatan yang bisa dijadikan untuk membunuh, dalam sekejap meredup. Berubah seperti mendung yang disusul dengan cucuran air hujan. >“Kami benar-benar sudah tidak nyaman hidup di tempat ini. Betapa tidak, hidup sedikit kaya, diusik, dimaling, digarong, dibegal. Tetapi sebaliknya, hidup susah hanya menjadi bulan-bulanan, dan bahan olok-olokan. Tempat macam apa ini?” Seorang warga meratap, sambil meletakkan tombak di atas tanah, di depan puing-puing rumahnya yang sudah hampir rata dengan permukaan tanah. >Seorang yang lain lagi tidak kalah sedihnya, pun menanggalkan golok dari tangannya. Matanya yang semula garang, menjadi sayup, disusul dengan genangan air mata yang merembas ke pipi, dan jatuh ke tanah, yang memang sudah basah oleh tangis anak, isteri, dan sanak saudaranya yang sedang sembunyi di kampung-kampung sebelah. >“Kalau manusia-manusia bencoleng itu tidak liar, dan membuat kehidupan Kami menjadi resah, semua tidak akan begini jadinya. Bayangkan saja, begitu mudah mereka bisa menenteng locok, menakut-nakuti Kami, untuk selanjutnya menjarah barang-barang Kami. Negeri macam apa ini? Lebih baik ditembaki saja mereka, ketimbang hidup merepotkan, dan meresahkan manusia lainnya! Atau, dikerangkeng saja, dan jangan biarkan mereka keluar lagi. Biarkan mereka hidup di dalam penjara!” >Terus, dan terus mereka mengeluhkan apa yang sedang terjadi. > >Kampung yang ludes bagai Padang Kurukhsetra itu, menjadi semakin mencekam. Orang-orang dari kampung yang disangkakan sebagai kampung para bencoleng, sudah bergerak pulang, dengan kemenangan. Dua, tiga, hingga empat hari kemudian, kampung itu menjadi semakin mencekam. Namun, memasuki hari ke lima; satu, dua, tiga, puluhan, bahkan ratusan penghuni kampung mulai berdatangan. >Tak ada cerita lain selain bagaimana ia menahan rasa takut saat orang-orang yang disangkakan dari kampung para bencoleng itu merangsek dan mengobrak-abrik kampungnya. Atau, cerita menahan rasa lapar lantaran sampai berhari-hari tidak ada yang berani keluar kampung, karena bersembunyi ke dalam alas, sebab tidak memiliki sanak-saudara sebagai tumpangan untuk berlindung. >“Kepala kampung ke mana, kok belum nampak?” Salah seorang warga kampung menanyakan kepada warga lainnya. >Sampai detik ini, saya juga belum melihat,” jawab warga yang lain. >“Rumahnya juga masih nampak sepi,” tandas warga yang lain lagi. >Terang saja, tidak munculnya kepala kampung pasca kerusuhan di tanah konflik tersebut menjadi pertanyaan besar bagi warga. Terlebih, sebelum puncak penyerangan itu terjadi, tepatnya ketika salah seorang warga yang disangkakan sebagai pencuri sapi itu di-geladak masa, sang kepala kampung pula yang memberikan komando. Lalu, ke mana sang kepala kampung? >Laki-laki ini adalah Saniman. Bukanlah sebagai pahlawan, bukan juga sebagai penyelamat, karena semua sudah terlanjur menjadi bubur. Orang yang disangkakan sebagai pencuri sapi sudah kadung 'lewa' nyawanya, terlebih dengan kampung itu sendiri, sudah kadung mirip dengan perkampungan di sekitar Jalur Gaza, yang nyaris ludes dibombardir oleh tentara Israel. >Dalam pengakuannya saat diintrogasi oleh anggota kepolisian pasca bentrok, Saniman mengaku, orang yang tewas digebuki, lalu disiram bensin dan dibakar itu berhutang uang dengan kepala desa. “Dia tidak mencuri, tapi menagih hutang. Kepala kampung jengkel, teriak malaing," aku Saniman. > Dan, memang begitulah; kesalahan terkadang bisa menjadi 'dosa' yang sulit diampuni, meskipun itu adalah masa lalu yang usang dan tidak akan pernah kembali lagi. Orang yang ludes digeladak masa itu adalah bagian dari orang-orang yang pernah salah, dan masih melekat di benak orang-orang yang kampungnya sudah setengah ludes. (* >Cerpen oleh: Wied H Soemardjono