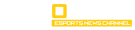Menelusuri Sejarah Demokrasi Terpimpin dan Dampaknya bagi Indonesia, Dari Pembangunan Jakarta Sampai Keterlibatan Militer dalam Politik
Senin, 03 Februari 2025 -
MerahPutih.com - Halo, Guys! Bayangkan kamu menikmati pagi yang cerah di Jakarta. Kamu menuju ke Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK) dengan melewati Jembatan Semanggi.
Lalu setelah sampai di GBK, kamu mengitari lingkar luarnya beberapa putaran. Setelah itu, kamu cari makan ke arah Grogol dan melewati Gedung DPR/MPR.
Tahukah kamu bahwa tiga bangunan itu punya satu keterkaitan?
Ya, semuanya dibangun pada era 1960-an, pada sebuah masa yang disebut Demokrasi Terpimpin (1959-1966).
Sepanjang masa ini, kuasa Presiden Sukarno sangat besar. Apalagi ditambah dengan dukungan dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia/Angkatan Darat (ABRI/AD) dan Partai Komunis Indonesia (PKI).
Sukarno menggagas banyak hal, termasuk perubahan wajah Jakarta dengan membangun gedung bertingkat dan monumen-monumen di berbagai jalan, Stadion GBK, Jembatan Semanggi, Gedung DPR/MPR, dan banyak lagi.
Bagi Sukarno, Indonesia harus jadi bangsa dan negara yang besar. Ia mesti jadi contoh bagi bangsa-bangsa lain yang masih berjuang melawan neoimperialisme dan neokolonialisme.
Sukarno menuangkan banyak gagasannya tentang masa depan Indonesia di kota Jakarta.
Di sinilah, di tengah hiruk-pikuk kota yang enggak pernah tidur, kita diingatkan akan babak penting dalam sejarah kita: Demokrasi Terpimpin.
Bagaimana Demokrasi Terpimpin bermula dan apa latar belakangnya, itu akan jadi bahasan kita kali ini.
Yuk, mulai.
Baca juga:
Sejarah Program Makan Bergizi Zaman Sukarno, Menggugah Kesadaran Gizi Anak Sekolah
Kecakauan Demokrasi Parlementer
Sebelum datang masa Demokrasi Terpimpin, Indonesia berada dalam babakan Demokrasi Parlementer (1950—1959) yang penuh dengan pergantian kabinet/pemerintahan. Bisa disebut juga eranya partai-partai politik berjaya.
Mengapa disebut era jaya?
Karena partai politik menempatkan wakilnya di parlemen (legislatif) serta pemerintahan (eksekutif) sebagai menteri. Lalu parlemen juga bisa menjatuhkan kabinet atau perdana menteri.
Masa Demokrasi Parlementer juga ditandai dengan konflik antara pemerintah sipil dengan Angkatan Darat (AD). Sebabnya, AD menganggap pemerintah sipil terlalu banyak campur tangan dalam penunjukan pemimpin AD.
Selama masa ini pula, Sukarno enggak punya peran berarti dalam pemerintahan. Dia memang jadi Presiden, tapi enggak punya kekuasaan buat memerintah.

Wewenang Sukarno yang paling besar adalah menentukan orang yang bertugas membentuk kabinet yang disebut formatur. Ia juga boleh membubarkan parlemen.
Posisi Sukarno menurut UUDS (Undang-Undang Dasar Sementara) 1950 adalah kepala negara, bukan kepala pemerintahan yang dijabat oleh perdana menteri. Ibarat kata, dia cuma jadi simbol doang.
Oya, sesuai namanya, UUDS 1950 itu berlaku sementara, selama belum ada UUD baru yang menggantikan UUD 1945.
Tugas menyusun UUD baru itu diserahkan ke sebuah dewan yang namanya Dewan Konstituante. Anggotanya dipilih lewat Pemilu 1955.
Selain Konstituante, anggota dewan atau parlemen juga dipilih lewat Pemilu 1955. Mereka menjadi anggota parlemen melalui partai politik.
Hasil Pemilu 1955 menempatkan Partai Nasional Indonesia (PNI), Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi), Nahdlatul Ulama (NU), dan PKI sebagai empat partai besar yang berhak mengisi parlemen dengan perolehan 50-30 kursi.
Semakin banyak kursi artinya semakin banyak pemilih partai tersebut.
Sisanya adalah partai-partai kecil seperti Partai Sarikat Islam Indonesia, Partai Kristen Indonesia, Partai Katolik, dan Sosialis Indonesia (PSI) dengan perolehan 8-5 kursi.
Berdasarkan hasil pemilu itu pula kabinet bakal disusun. Orang-orang yang jadi menteri berasal dari partai-partai yang punya kursi, terutama empat partai besar.
Pemilu 1955 ini sangat diharapkan oleh masyarakat sebagai jalan keluar kacaunya kondisi politik. Salah satu ukurannya adalah gonta-ganti kabinet sebanyak lima kali sejak 1950 hingga 1955.
"Keadaan ini dilihat dari krisis-krisis kabinet yang berulang, tantangan angkatan darat terhadap wibawa pemerintah, korupsi, nepotisme politik, pertikaian antarpartai," kata Herbert Feith, seorang pakar politik yang meneliti sejarah Indonsia pada 1950-an, dalam bukunya Pemilihan Umum 1955.
Baca juga:
Apa sih Guna Sejarah? Dari Mengangkat Orang-Orang Kecil sampai Fondasi untuk Bangun Masa Depan
Pergolakan Daerah dan Konsepsi Presiden 21 Februari 1957
Namun, harapan itu ternyata enggak mewujud. Kabinet hasil Pemilu 1955 yang dipimpin oleh Ali Sastroamijoyo dari PNI pun bisa dijatuhkan parlemen pada 14 Maret 1957.
Sebelum kabinet itu jatuh dan terbentuk, Sukarno sebenarnya berharap supaya kabinet melibatkan empat partai pemenang Pemilu 1955.
Kabinet itu disebut juga 'Kabinet Kaki Empat'. Namun, Kabinet Ali enggak mengikutsertakan PKI. Jadilah, kabinetnya dianggap pincang.
Sukarno pun kecewa berat.
"Saudara sebagai formatur bersikap tidak adil terhadap PKI. Mengapakah suatu partai besar yang mendapat suara dari rakyat lebih dari 6 juta itu, tidak kau ikut sertakan dalam kabinet baru! ini tidak adil," kata Sukarno, seperti diceritakan oleh Ali Sastroamijoyo dalam otobiografinya, Tonggak-Tonggak di Perjalananku.
Kabinet Ali Sastroamijoyo jatuh karena kegagalan mereka menangani pergolakan di daerah.
Sepanjang 1956, pemimpin daerah-daerah di luar Jawa seperti Sumatera dan Sulawesi mulai menyatakan adanya ketimpangan pembangunan antara Jawa dan luar Jawa.

Keadaan ini diperparah oleh mundurnya Mohammad Hatta dari wakil presiden pada 1 Desember 1956. Padahal Hatta dianggap perwakilan orang-orang luar Jawa.
"Pada akhir tahun 1956 ada krisis yang luar biasa. Macam-macam hal terjadi. Bukan hanya karena daerah mulai main sendiri, tetapi juga karena ada pertentangan antara Bung Karno dan Bung Hatta," kata Daniel S. Lev, pakar politik Indonesia dari AS, seperti termuat dalam buku Mencari Demokrasi.
Daniel juga menambahkan, saat itu ketertarikan dan peran AD dalam politik mulai meningkat. Apalagi setelah Mayjen A.H. Nasution menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Darat (KASAD).
"Pimpinan tentara menganggap orang sipil yang membuat keadaan kacau kemudian tidak bisa menyelesaikan kekacauaan itu," sebut Daniel.
Di tengah krisis itu, Sukarno mengeluarkan Konsepsi Presiden 21 Februari 1957. Secara sederhana, konsepsi itu berarti serangkaian gagasan buat menyelesaikan masalah.
Isi Konsepsi Presiden 21 Februari 1957 secara umum ada dua. Pertama, pembentukan sistem pemerintahan baru berupa kabinet gotong royong yang menyertakan PKI. Kedua, pembentukan Dewan Nasional yang terdiri dari wakil-wakil golongan fungsional dan dipimpin oleh Presiden Sukarno.
Golongan fungsional itu kelompok masyarakat yang hidup dan membentuk negara Indonesia. Misalnya buruh, petani, cendekiawan, tokoh agama, perempuan, pemuda, daerah, angkatan 1945, pengusaha, dan ABRI.
Konsepsi Sukarno ini melengkapi kritiknya terhadap sistem Demokrasi Parlementer yang menurutnya diadopsi dari Barat, sumber perpecahan, dan enggak cocok dengan kepribadian masyarakat Indonesia.
"Pada bulan Oktober 1956, ia menyatakan bahwa semua partai politik sebaiknya dikubur karena merupakan 'sumber' penyakit yang menyebabkan perpecahan bangsa," begitu menurut Adnan Buyung Nasution, penulis buku Aspirasi Pemerintahan Konstitusional di Indonesia.
Sebagai gantinya, Sukarno mengajukan tawaran Demokrasi Terpimpin.
Baca juga:
Mengenal Tritura, Suara Rakyat di Tengah Krisis Ekonomi dan Politik
Dukungan Militer AD untuk Demokrasi Terpimpin
Konsepsi Presiden 21 Februari 1957 rupanya enggak bikin partai politik tertarik. Mereka masih yakin bisa mengatasi masalah dan Demokrasi Parlementer adalah sistem yang baik.
Namun, AD, melalui jenderal pemikirnya, yaitu A.H. Nasution justru menganggap sebaliknya. Mereka kepincut banget dengan gagasan Demokrasi Terpimpin.
Apalagi dalam Demokrasi Terpimpin ada gagasan golongan fungsional yang membuka peluang AD buat masuk ke politik dan pemerintahan.
Masalahnya adalah AD enggak mau main kudeta atau perebutan kekuasaan secara ilegal. AD ingin masuk ke politik dan pemerintahan berdasarkan undang-undang.
Nah, UUDS 1950 enggak memungkinkan AD bergabung dalam politik dan pemerintahan. Mereka pun melirik ke UUD 1945.
Menurut Nasution, Pasal 2 UUD 1945 dapat ditafsirkan sebagai pasal yang menentukan perwakilan golongan fungsional. Karena itulah, Nasution menginginkan UUD 1945 berlaku kembali.
"Bagi AD ini merupakan satu-satunya jalan untuk mempertahankan legitimasi perannya dalam politik nasional," terang Buyung Nasution.

Nasution lalu menggagas sebuah konsep buat memuluskan tentara bisa berpolitik dan masuk pemerintahan secara legal. Konsep itu disebut 'Jalan Tengah'.
Maksud 'Jalan Tengah' adalah AD enggak mau melakukan kudeta seperti di negara Amerika Latin, tapi juga enggak bisa diam saja secara pasif.
Nasution mendesak supaya perwira memperoleh kesempatan buat berpolitik dan menentukan kebijakan ekonomi, keuangan, internasional dan lain-lain. Konsep ini kelak pada masa Orde Baru disebut Dwi Fungsi ABRI.
"Nasution mengancam bahwa kalau ini tidak diberikan, tidak dapat dijamin bahwa AD akan menolak jalan kekerasan untuk mencegah diskriminasi terhadap perwira-perwiranya," ungkap Daniel.
Sukarno semula enggan balik ke UUD 1945, tapi posisinya mulai melemah setelah tentara memainkan peran penting dalam penumpasan pergolakan daerah di Sumatra (PRRI/Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia) dan Sulawesi (Permesta/Perjuangan Rakyat Semesta) pada 1958.
Baca juga:
Demo Mahasiswa 1966, Ketika Suara Anak Muda Mengubah Sejarah Indonesia
SOB dan Dekrit Presiden 5 Juli 1959
Melalui Undang-Undang Keadaan Darurat Perang (SOB/Staat van Orlog en Beleg) yang dikeluarkan pada 14 Maret 1957, hari yang sama ketika Kabinet Ali Sastroamijoyo jatuh, tentara mulai mengambil alih pemerintahan sipil.
"Dengan diberlakukannya Undang-Undang Keadaan Bahaya (SOB) dalam bulan Maret, maka Kepala Staf Angkatan Darat Nasution menjadi Penguasa Perang Pusat, para panglima wilayah menjadi Penguasa Perang Daerah, dan para komandan tentara di berbagai tingkat yang lebih rendah memperoleh kekuasaan baru di dalam pemerintahan setempat," urai Herbert Feith dalam bukunya Soekarno-Militer dalam Demokrasi Terpimpin.
Dari sini, tentara mulai berlaku keras kepada partai politik. Mereka melarang pertemuan politik, memberangus pers, dan menangkap menteri serta tokoh politik.
Karena undang-undang itu pula, PSI dan Masyumi yang menolak gagasan Presiden Sukarno tentang Demokrasi Terpimpin, dibabat habis dan enggak boleh berkiprah lagi.

Nah, karena posisinya dirongrong tentara, Sukarno mendekat ke PKI yang mendukung gagasan Demokrasi Terpimpin. Dia menggunakan PKI buat penyeimbang tentara.
Berkat dua kekuatan itulah, akhirnya pada 5 Juli 1959 Sukarno mengeluarkan Dekrit Presiden.
Isi Dekritnya, pembubaran Dewan Konstituante yang dianggap gagal membuat UUD baru, kembali ke UUD 1945, dan pembentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) dan Dewan Pertimbangan Agung Sementara (DPAS).
Dekrit inilah yang mengakhiri masa Demokrasi Parlementer sekaligus mengawali masa Demokrasi Terpimpin.
Dekrit Presiden 5 Juli 1959 bikin pengaruh dan karisma Sukarno terus membesar. Sukarno dianggap sebagai penyelamat negara setelah masa Demokrasi Parlementer yang banyak pertikaian politik dan pergolakan daerah.
Kata Daniel, Sukarno "Mulai merasa diri menjadi orang yang sangat penting, sangat besar, sangat, sangat.’’
Sukarno dapat kesempatan menuangkan gagasan besarnya. Beberapa di antaranya diwujudkan lewat bangunan-bangunan di Jakarta.
Kelihatan kan sekarang betapa politik punya pengaruh besar dalam sejarah Indonesia, termasuk menciptakan sarana olahraga, jalan raya, dan perkantoran seperti GBK, Jembatan Semanggi, dan gedung DPR/MPR. (dru)
Baca juga:
Manusia sebagai Subjek, Objek, dan Saksi Sejarah, Mengungkap Kisah di Balik Perubahan Zaman